 Tahun pertama di Jatinangor saya rasa adalah tahun yang mengagetkan bagi setiap orang. Setelah di elu-elukan keluarga karena masuk UNPAD, saya dihadapkan dengan rentetan kenyataan. Bahwa saya tidak lagi dekat dengan keluarga, bahwa saya harus beradaptasi & harus membiasakan diri punten akang, punten teteh tiap melintasi sudut kampus. Waktu itu bulan puasa sama seperti sekarang. Sama pula seperti sekarang, bulannya yang berpuasa. Saya sibuk menggantungkan kaki di warteg. Keberengsekan yang tidak pernah luntur.
Tahun pertama di Jatinangor saya rasa adalah tahun yang mengagetkan bagi setiap orang. Setelah di elu-elukan keluarga karena masuk UNPAD, saya dihadapkan dengan rentetan kenyataan. Bahwa saya tidak lagi dekat dengan keluarga, bahwa saya harus beradaptasi & harus membiasakan diri punten akang, punten teteh tiap melintasi sudut kampus. Waktu itu bulan puasa sama seperti sekarang. Sama pula seperti sekarang, bulannya yang berpuasa. Saya sibuk menggantungkan kaki di warteg. Keberengsekan yang tidak pernah luntur.
Bagi mereka yang tumbuh besar di kota-kota megapolitan atau semi-megapolitan, terdampar di Jatinangor nyaris menjadi kutukan. Setidaknya di tahun 2011 saya melihat. Semua orang sibuk membiasakan diri. Dari mulai membiasakan makan dengan tikus melintas di Hipotesa (dulu, saya harap sekarang tidak), berburu tempat sampah plastik di sabar subur sampai ngeceng di Brooklyn gerbang lama Unpad. Melihat teteh-teteh bermasker karena wajahnya jerawatan. Kemungkinan besar karena air dan udara di kotanya jauh berbeda dengan di Jatinangor.
Apabila anda di sekitar tahun 2011 adalah anak Fikom seperti saya, anda pasti akrab dengan sebuah payung bermerek minuman the dalam botol di kantin. Konon kabarnya, para macan kampus bersemayam di sana. Lengkap dengan segala kisah mistis politis mereka. Saya tidak ambil pusing. Mau bajingan setengik apapun, saya akan baik pada orang yang baik pada saya. Kebetulan mereka baik pada saya. Sebagai anak bawang, saya tentu senang sekali mendengar bagaimana mereka mengkisahkan kampus ini. Kisah yang tidak saya dapat ketika proses penataran. Mungkin karena pertimbangan moral para panitia.
Banyak dari mereka adalah musisi. Entah memang sudah stigma yang melekat atau memang kebetulan saja. Akang-akang gondrong berparka dengan ideologi sinting dan mendalami musik. Seperti memang selalu seperi itu penyajiannya. Namun siapa sangka, dari selingan diskusi musik di tengah pembahasan politik kampus saya dipertemukan dengan sebuah lagu. Sejak itu lagu ini menjelma menjadi blueprint bagaimana saya bersikap hingga hari ini.
Dua chords. E mayor dan A mayor. Itu yang Galih butuhkan untuk menyulap sebuah puisi dari Chairil Anwar menjadi sebuah kredo bagi saya. Buat Gadis Rasid yang saya temukan “dinyanyikan” oleh Galih pada tahun 2011 versi mentahnya dan versi albumnya beberapa tahun kebelakang sukses bertengger di hidup saya. Abadi. Entah bagian mananya. Galih hanya memainkan gitar kopong pada versi mentahnya. Memetiknya dengan tempo yang lambat. Suaranya mengalun di tengah kerongkongan atas. Diayun dengan nada khas folk kedaerahan tahun-tahun 2011 sebelum genre ini diperkosa oleh industri musik. Namun jika ada yang bertanya dimana titik awal pendakian hidup saya maka Jatinangor dan lagu ini adalah markanya.
Puisinya sendiri keluar pada tahun 1948. Tentang seorang wartawan yang tetap berdiri tegak dengan idealismenya. Ditengah gempuran badai revolusi pada waktu itu. Dibukukan oleh Chairil Anwar pada Aku ini Binatang Jalang. Berharap seperti Gadi Rasid, saya berharap idealisme saya tidak luntur ditelan kebutuhan beli handphone terbaru. Itupun kalau saya dan ribuan bahkan jutaan orang di Jatinangor dulu hingga kini pernah punya idealisme.
Saya takut jangan-jangan kepemilikan idealisme memang hanya desas-desus yang sudah lama mati. Jangan-jangan bagi kita yang pernah menjejakan kaki di Jatinangor hidup hanya proses linear yang gampang terlupakan. Semua harus otomatis seperti eskalator. Masuk kampus negri kenamaan lalu memperkaya diri sebanyak-banyaknya. Sebuah asumsi yang durhaka tentu dari saya. Meski begitu saya senang menyimpan ketakutan itu. Ketakutan membuat kita jadi bersiap dengan kemungkinan terburuk. Lagu ini dari 2011 sampai nyaris satu dekade kemudian adalah pengingat bagi saya. Bahwa tidak memperlakukan hidup seperti bisnis yang harus menghasilkan keuntungan saja.
Setelah saya dewasa saya berkesempatan untuk bertemu dengan Galih. Di tempat yang cukup absurd. Di reruntuhan rumah-rumah warga yang tergusur di pojokan Dago Kota Bandung. Musiknya Galih mengantarkan saya kesana. Bertemu dengan Galih secara langsung. Di sebuah lapangan voli yang disulap menjadi panggung solidaritas. Bila momen saya bertemu dengan Galih adalah demikian, maka Galih perlu tau bahwa musiknya berhasil mengantarkan satu orang pada hal yang dia percayai dan perjuangkan. Dengan baiknya Galih juga mengajak saya ke panggung untuk bermain harmonika secara spontan di lagu terakhirnya. Sesuatu yang akan mencengangkan diri saya yang berada di tahun 2011. 




















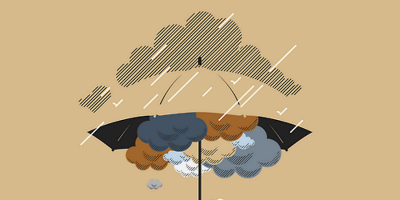
KOMENTAR ANDA