 Acap kali kita temui pasangan kata “mahasiswa-mahasiswi”, “siswa-siswi” “saudara-saudari”, “muda-mudi”, “dewa-dewi” dan sebagainya di masyarakat. Kata-kata tersebut tidak asing karena sering digunakan oleh masyarakat terutama dalam ragam bahasa pendidikan.
Acap kali kita temui pasangan kata “mahasiswa-mahasiswi”, “siswa-siswi” “saudara-saudari”, “muda-mudi”, “dewa-dewi” dan sebagainya di masyarakat. Kata-kata tersebut tidak asing karena sering digunakan oleh masyarakat terutama dalam ragam bahasa pendidikan.
Pasangan kata tersebut memiliki pasangan semantik atau makna yang sama, tetapi memiliki perbedaan hanya pada alamat jenis kelamin. Kata “siswa” dirujukkan untuk pelajar berjenis kelamin laki-laki, sedangkan kata “siswi” dirujukkan untuk pelajar berjenis kelamin perempuan. Hal ini pula berlaku untuk pasangan kata yang lain.
Dalam dunia akademik, kita kerap menjumpai lembaga mahasiswa yang dinamai “Badan Eksekutif Mahasiswa” dan “Badan Perwakilan Mahasiswa”. Namun, tidak pernah sekalipun saya jumpai adanya lembaga kampus yang diberi nama “Badan Eksekutif Mahasiswi” maupun “Badan Perwakilan Mahasiswi”.
Lagian, rasanya aneh juga. Tentu saja bila kita mengunjungi lembaga tersebut, sebagai contoh lembaga Badan Eksekutif Mahasiswa, dapat kita jumpai bahwa lembaga tersebut terdiri dari pengurus laki-laki dan perempuan.
Lho kok? Timbulah pertanyaan semantik-filosofis yang mengajak kita merenung, bagaimana mungkin dalam lembaga tersebut bisa terdiri dari pengurus laki-laki dan perempuan. Padahal nama lembaga tersebut “Badan Eksekutif Mahasiswa” yang, bila mengacu pada kesepakatan makna, seharusnya berisikan pengurus laki-laki saja.
Bahasa yang Uniseks
Bahasa Indonesia adalah bahasa yang unisex atau dapat dikatakan bahasa yang tidak mengenal jenis kelamin. Perhatikan saja, kata ganti orang ketiga dalam bahasa Indonesia merupakan kata yang umum. Kata “dia” tidak jelas merujuk pada jenis kelamin tertentu. Kata “dia” bisa merujuk pada dia laki-laki, bisa juga merujuk pada dia perempuan. Sementara itu, bahasa Indonesia yang uniseks mengakibatkan morfologis kata yang uniseks pula. Kata “nya” sebagai kepemilikan tidak jelas merujuk pada jenis kelamin tertentu.
Hal ini berbeda dengan bahasa Inggris yang mengenal jenis kelamin. Kata ganti orang ketiga dalam bahasa Inggris dibagi menjadi “he” untuk dia yang berjenis kelamin laki-laki dan “she” untuk dia yang berjenis kelamin perempuan. Hal ini berpengaruh pada proses morfologis bahasa Inggris yang menciptakan kata “her/his” untuk kepunyaan dia berdasarkan jenis kelamin, dan kata “him/her” untuk mengacu pada dia berdasarkan jenis kelamin dalam kalimat pasif.
Lain lagi dengan bahasa Arab yang mengklasifikasikan kata ganti orang ketiga dengan begitu spesifik, yakni berdasarkan jenis kelamin dan berdasarkan jumlah. Kata ganti orang ketiga dibagi menjadi enam, yakni: “huwa” (satu orang laki-laki); “huma” (dua orang laki-laki); “hum” (lebih dari dua orang laki-laki); “hiya” (satu orang perempuan); “huma” (dua orang perempuan); dan “hunna” (lebih dari dua orang perempuan).
Bahasa Indonesia yang uniseks berdampak pada ketidak-adanya klasifikasi makna berdasarkan jenis kelamin. Makna kata “mahasiswa” tidak merujuk pada jenis kelamin tertentu. Kata “mahasiswa” secara etimologis, memiliki makna orang yang berlajar di perguruan tinggi, dan makna tersebut sudah mencakup makna pelajar laki-laki dan pelajar perempuan. Hal ini berlaku juga untuk kata “saudara”, “dewa”, dan sebagainya.
Feminisasi Bahasa
Secara historis, bahasa di belahan dunia manapun mengalami feminisasi. Hal ini dilandaskan pada gagasan feminis yang ingin memperjuangkan emansipasi hingga taraf substansi bahasa karena diannggap diskriminatif atas ketimpangan gender. Sementara itu, bahasa Indonesia yang mengalami feminisasi cenderung dipengaruhi oleh faktor sosiobudaya dan semantis.
Sebagai contoh, kata “wanita” populer digunakan pada masa Orba sedangkan kata “perempuan” populer digunakan pada masa pasca Orba. Hal ini diakibatkan oleh fungsi makna yang dianggap mendiskreditkan. Makna kata “wanita” dianggap mendiskreditkan karena berasal dari gabungan bahasa Jawa, yaitu kata “wani” yang berarti berani dan kata “di-tata” yang berarti diatur.
Adapula kelompok yang menganggap diskredit karena berasal dari gabungan kata bahasa Inggris, yaitu kata “want” dan “it” yang berarti benda yang dihasratkan. Selain itu, kata “wanita” dianggap sebagai bentuk represi rezim Orba yang menginginkan konstruksi perempuan yang ideal, yakni perempuan yang menerima kodratnya berdasarkan nilai patriarkis.
Pasca Orba, kata “wanita” kemudian diganti dengan padanan kata “perempuan” yang dianggap lebih memiliki citarasa makna yang lebih positif. Kata “perempuan” secara etimologis berasal dari kata “empu” yang mendapat konfiks “per” dan “an” yang memiliki makna orang yang ahli. Kata “perempuan” ini diharapkan membawa citra positif yang lebih mewakili kelompok perempuan.
Sementara itu, aspek kebahasaan yang lain seperti fonologi menjadi salah satu metode feminisasi bahasa. Misalnya, dalam fonem /a/ dapat menandai gender maskulin, sedangkan fonem /i/ menandai gender feminin seperti terdapat pada pasangan kata “mahasiswa-mahasiswi”. Hal ini didasari bahwa pelafalan fonem /a/ yang menyebabkan mulut terbuka sepenuhnya dianggap terlalu vulgar dan tidak mewakili perempuan.
Oleh sebab itu, feminisasi bahasa perlu dibicarakan pada ruang yang lebih luas. Terlepas dari kelebihannya yang menambah khazanah pembendaharaan kata bahasa Indonesia dan kekurangannya yang membuat kebingungan makna.











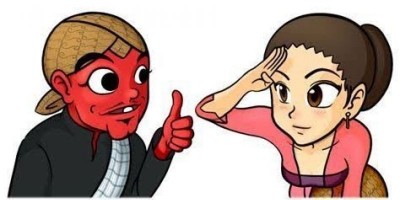








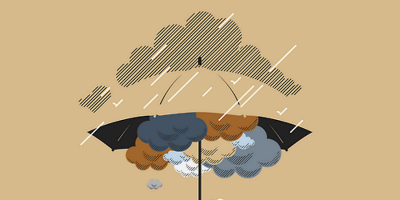
KOMENTAR ANDA