 Acap kali ketika berselancar di dunia maya, saya tersesat pada situs agamis yang mengajak untuk menikah muda. Biasanya, caption atau kata-katanya sangat persuatif semisal: “ibadah kok sendiri?”, “nikmatnya berdua menuju surga”, atau yang lebih sedikit menyerang “umur 17 tahun bukan daftar SMA, tapi daftar KUA”.
Acap kali ketika berselancar di dunia maya, saya tersesat pada situs agamis yang mengajak untuk menikah muda. Biasanya, caption atau kata-katanya sangat persuatif semisal: “ibadah kok sendiri?”, “nikmatnya berdua menuju surga”, atau yang lebih sedikit menyerang “umur 17 tahun bukan daftar SMA, tapi daftar KUA”.
Biasanya, caption yang membersamai adalah foto pasangan muda-mudi yang tengah tersenyum bahagia pada saat resepsi pernikahan, atau telah menikah sambil si istri menggandeng tangan suaminya yang menggendong anaknya, atau tengah foto pranikah menunjuk langit yang sebenarnya tidak ada apa-apa di sana.
Kata-kata seperti ini, yang sampai ke benak pembaca remaja dan dewasa muda, membuat mereka rentan sekali insecure sebab jomlo atau single seolah merupakan kesalahan yang berdosa.
Saya tidak punya masalah dengan orang yang menikah muda, toh saya apresiasi mereka karena berani mengambil keputusan yang besar di hidupnya pada usia muda. Akan tetapi, yang menjadi masalah adalah ketika nikah muda mengakibatkan pengambilan keputusan terburu-buru, menggiring pada problem finansial dan mental yang biasanya berujung pada kekerasan rumah tangga.
Ketergesaan nikah muda ini dapat kita bayangkan seperti kita sedang ujian, kemudian satu persatu peserta ujian keluar ruangan telah menyelesaikan ujian sedangkan kita yang belum selesai menjawab semua soal seolah diserang kepanikan dan ingin buru-buru mengumpulkan lembar jawaban padahal waktu ujian yang tersisa masih banyak.
Keresahan ini bermula ketika sekian banyak kolega perempuan saya semasa kuliah kerap mengeluh tentang sulitnya tugas kuliah yang diberikan. Keluhan mereka selalu bernada candaan, semisal “pusing ah, mending nikah aja udah”, tetapi siapa tahu kalau beberapa dari mereka yang mengeluh demikian ada yang tidak bercanda.
Studi Kasus
Data dari Hasil Survei Demografi dan Kependudukan Indonesia (SKDI) pada 2008 hingga 2012 menunjukkan ada 340 ribu kasus pernikahan anak (di bawah usia 18 tahun) per tahun. Survei UNICEF menunjukkan bahwa tradisi, agama, kemiskinan, ketidaksetaraan gender, dan ketidakamanan karena konflik adalah alasan utama tingginya jumlah perkawinan anak-anak di Indonesia.
Nikah muda memberikan dampak negatif berupa kematian bagi perempuan karena problem kematangan organ reproduksi. Alasan belum matangnya organ reproduksi didukung data dari Kementerian Kesehatan yang menunjukkan angka kematian ibu di Indonesia karena melahirkan, kehamilan, dan nifas terus mengalami peningkatan yaitu 4.525 kasus pada 2014, 4.890 kasus pada 2015, dan 4.912 kasus pada 2016.
Sedangkan menurut Survei Penduduk Antar Sensus 2016, angka kelahiran ibu mencapai 305 per 100.000 kelahiran hidup dan angka kelahiran balita 22 per 1.000 kelahiran hidup. Angka ini termasuk yang tertinggi di antara anggota Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN).
Dengan statistik di atas, nikah muda tepat dikatakan “keliru” sebab praktik menikah muda tidak mengindahkan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) Tentang Perkawinan terkait batas usia perkawinan anak. Batas usia menikah yang telah direvisi adalah 20 tahun bagi laki-laki dan 18 tahun bagi perempuan. Selain itu, praktik nikah muda yang sering ditemui di masyarakat telah mencederai UUD 1945 yang memberi hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan.
Sindrom Cinderella Akibat Nikah Muda
Pasangan yang menikah muda rentan mengalami kekerasan rumah tangga sebab belum matangnya psikis tiap-tiap individu. Sementara itu, nikah muda yang dipantik oleh tren urban akan melahirkan sindrom Cinderella khusus pada diri perempuan. Dampak lain akibat ketidakmatangan psikis perempuan menyikapi pernikahan muda.
Sindrom Cinderella pertama kali dikemukakan oleh Collete Dowling pada tahun 1981 melalui bukunya yang kemudian dialihbahasakan oleh Santi W. E. Soekanto pada tahun 1989 berjudul Cinderella Complex: Ketakutan Perempuan akan Kemandirian. Menurut Dowling, perempuan memiliki kecenderungan ketergantungan yang tersembunyi dan terkubur dalam alam bawah sadar.
Dowling mendefinisikan sindrom Cinderella sebagai sebuah jaringan sikap dan rasa cemas akan kemandirian yang membuat psikis perempuan tertekan (insecure). Definisi mandiri yang dimaksud Dowling adalah kemamuan untuk mengeksplor pontensi diri, kemampuan bergantung pada diri sendiri dalam membuat keputusan, kepahaman pada kapasitas diri, dan kemampuan mengolah potensi diri menjadi sebuah keuntungan atau profit. Perasaan enggan dan cemas akan kemandirian ini dialami oleh perempuan yang telah bersuami.
Sebagaimana tokoh Cinderella dalam cerita rakyat, perempuan memilih jalur alternatif dengan cara menantikan seorang pangeran yang akan menyelamatkan dirinya dari kesengsaraan dan ketidaknyamanan. Dowling menjelaskan sindrom Cinderella muncul dalam bentuk keinginan yang mendalam untuk dirawat dan dilindungi oleh laki-laki.
Perasaan enggan dan cemas yang dialami perempuan tersebut mengakibatkan timbulnya kebutuhan psikologis untuk menghindari kemandirian dan keinginan untuk diselamatkan. Parahnya, hal ini dinormalisasi oleh budaya kita yang patriarkis karena peran gender dalam rumah tangga yang menempatkan laki-laki sebagai kepala rumah tangga yang bertugas melindungi dan mengayomi sedangkan perempuan sebagai yang dilindungi dan yang diayomi. Akibatnya, ideologi feminitas seperti ini menjadikan perempuan mencerap status inferior mereka sehingga tidak dapat mengembangkan potensi diri yang paripurna.
Oleh sebab itu, alangkah baiknya jika pilihan menikah diputuskan atas pertimbangan kematangan mental, fisik, dan finansial. Sangat disayangkan jika pilihan menikah diputuskan karena tren di Instagram semata atau apalagi karena ikut-ikutan teman.


















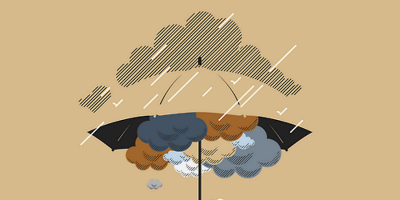
KOMENTAR ANDA