 Langit.
Langit.
Hari ini kau tepat berusia dua puluh satu. Ibumu tahu aku tidak pernah suka atau menyempatkan diri merayakan waktu. Aku lebih suka merayakan hari ini, marayakan kehidupan dan syukur-syukur bisa merayakan kebahagiaan sebagaimana yang sering diidamkan banyak orang.
Aku bertemu ibumu di sebuah bar, dia bartender di sana. Kami tidak pernah banyak bicara. Hubungan kami sederhana, hubungan seorang pembeli dan penjual biasa. Malam itu aku duduk di kursi bar paling ujung, di depanku ada segelas minuman yang belum sempat aku cicipi. Ibumu datang kearah mejaku, dan langsung bertanya "Kenapa datang hari rabu?". Pertanyaan itu cukup wajar keluar, aku biasanya hanya datang ke sana setiap hari Jumat. Sudah puluhan Jumat malam aku habiskan di sana. Hanya melamun seorang diri. Aku tidak langsung menjawab, hanya menyalakan rokok. "Rabu dan Jumat tidak ada bedanya, kita yang memutuskan semua itu berbeda," jawabku setelahnya.
Ibumu duduk di sebelahku, katanya itu hari terakhir dia bekerja di sana. Pekerjaan menjadi bartender memang menyenangkan katanya, tapi banyak lelaki yang terus membuatnya muak dari hari ke hari. Aku sempat menanyakan apakah aku salah satu lelaki yang memuakan itu? Dia tidak menjawab. Ibumu membelikanku minuman yang lain, katanya sebuah minuman perpisahan, karena mungkin kita tak akan pernah bertemu lagi. Aku menerimanya dengan senyum, lantas berpikir kenapa perpisahan bisa semenyenangkan ini. Iya, itu malam yang menyenangkan. Kami membicarakan banyak hal, dan ibumu selalu punya energi untuk menceritakan banyak hal. Lalala-lalala... kata itu terus diulang ibumu setiap kali dia berusaha menjelaskan sesuatu padaku.
Ini terasa aneh bagiku. Aku puluhan kali datang ke sini. Bar yang tidak terlalu hingar bingar, hanya lampu temaram dan lukisan yang aku tidak aku pahami menempel di dindingnya. Dari puluhan kesempatan untuk bertemu dengan ibumu, hanya malam itu dia menyempatkan diri, untuk bicara dan mengucap kata perpisahan.
Malam itu kami berpisah dengan gelak tawa. Minggu selanjutnya aku datang lagi ke bar tersebut, duduk di tempat yang sama dengan minuman yang sama seperti yang ibumu pesankan minggu sebelumnya. Aku tidak melamun malam itu, aku hanya memandang tempat kerja ibumu dulu dan mulai membayangkan dirinya hadir di sana, menyiapkan pesanan dengan rambut diikat agak berantakan. Pulang dari sana aku mencoba mencari tahu di mana ibumu tinggal. Beberapa minggu setelahnya, aku mengetuk pintu rumah berwarna merah. Ibumu membuka pintu, kami tersenyum.
Puluhan tahun yang lalu, aku pernah berjanji kepada ibumu, sebuah janji yang tidak bisa aku pahami sepenuhnya. Tapi aku tahu ibumu punya banyak alasan kenapa dia meminta itu padaku. Sebuah janji yang mengharuskan aku jadi bapak untuk anaknya kelak. Mungkin tampak membahagiakan jika kau membayangkan seorang perempuan meminta itu pada seorang lelaki. Yang kita tahu, biasanya permintaan semacam itu tentunya permintaan antara sepasang kekasih yang sedang dimabuk asmara.
Tetapi sialnya, keadaan kami berbeda. Kami tidak sedang hidup dalam sebuah dongeng utopis, yang di dalamnya ada sepasang kekasih yang bahagia karena dipertemukan dengan orang yang mereka cintai. Kami hidup di dunia yang terus menerus berusaha kami pahami. Dunia yang sejatinya terus memaksa kami untuk bertahan dan menguatkan diri. Dunia yang selalu abu dan kesedihan tampaknya membuat semua orang berubah menjadi jahat. Setidaknya itulah yang kami rasakan.
Dunia yang kami pahami saat itu hanya sebuah perjalanan menemukan kebahagiaan. Dan mempunyai anak dianggap sebuah jalan yang bisa menerangi kehidupan kami yang akan datang. Jalan menuju kebahagiaan yang cukup aneh, karena kami bukan pasangan suami istri. Kami hanya dua manusia yang tidak pernah mengerti tentang kebahagiaan itu sendiri. Kami hanya memanknai kebahagiaan sebagai sebuah anugrah Tuhan paling sempurna, kadang datang dengan cara yang sangat sederhana. Lewat senyum ibumu contohnya.
Langit, aku tidak begitu bisa menjelaskannya. Kenapa akhirnya Tuhan memberi kesempatan kepadaku untuk menjadi seorang bapak. Bapak dari anak yang tidak pernah diberi pengetahuan tentang siapa dan di mana bapaknya berada selama rentan waktu yang cukup panjang ini. Yang sampai saat ini tampak jelas di ingatanku hanya senyum ibumu yang berubah jadi tangis yang dapat melelehkan semua es di Kutub Selatan. Aku bahagia, ketika mengetahui dirinya hamil. Tangisannya terus menggema di kepalaku, tangisan seorang perempuan yang kebahagiaannya melebihi apapun yang bisa aku bayangkan.
Ketika itu terjadi, kebahagiaanku berubah menjadi perasaan takut yang aneh, aku memikirkan bahwa aku tidak akan dapat mengenali anakku sendiri. Nanti aku hanya akan jadi lelaki tua tanpa tahu anaknya. Lelaki tua yang hidup sendirian. Tapi ketika aku melihat ibumu, perasaan itu benar-benar menghilang. Setelah itu kami rutin mengunjungi dokter untuk memeriksakan perkembangan kehamilannya. Aku selalu berpura-pura menjadi suami siaga, dan kadang lebih siaga dari suami manapun yang bisa dilakukan lelaki manapun di kaki langit.
Aku ada di samping ibumu ketika ia ada di ruang persalinan, prosesnya cukup lancar, hanya beberapa jam saja. Tapi aku yakin ibumu tidak berpikir seperti itu, itu malam yang panjang untuknya, malam yang penuh peluh dan rasa sakit. Cengkraman ibumu sanggup meremukan jemariku waktu itu. Suara tangismu memecah kegelisahan kami di sana. Bayi merah dengan rambut selebat hutan hujan. Aku memangkumu, aku dekap penuh kebahagiaan, aku tempelkan di dadaku. Tangisnya reda dan aku tersenyum. Setelahnya, ibumu memintaku menyerahkan bayi itu, didekapnya erat dengan lelehan air mata yang membelah pipinya. Itu pertama kali aku menggendongmu, juga kali terakhir.
Kita sudah sepakat, aku hanya akan menemaninya sampai kau lahir. Aku melihatmu dari jendela kaca besar, kau dimasukan ke dalam akuarium kecil. Iya, aku lebih suka menyebutnya akuarium. Akuarium itu dilabeli namamu juga nama ibumu, tak ada namaku di sana. Setelahnya aku melihat ibumu, ia tidur begitu pulas, dengan sisa-sisa kebahagiaan yang masih terpancar di mukanya. Aku mencium kedua matanya, dan meninggalkan sepotong kertas dengan tulisan ‘Suatu saat aku akan melihat anakku dan perempuan hebat yang merawatnya penuh kasih.’
Sepanjang aku mengenal ibumu, aku hanya melihatnya menangis dua kali. Ketika dia tau dirinya hamil, dan ketika kau lahir. Dia perempuan hebat yang terus menerus membuatku kagum. Perempuan yang selalu yakin dapat mengurusmu seorang diri dan itu terbukti hingga hari ini.
Langit, aku selalu menanti saat ini dengan penuh keraguan. Apakah aku masih hidup dan mempunyai cukup kewarasan untuk menemuimu? Apakah kau akan mampu mengenali diriku? Apakah ikatan ayah dan anak itu persis seperti yang digambarkan di banyak buku dan film? Aku menunggu saat ini dengan kecemasan yang selalu tak mampu aku jabarkan seluruhnya.
Aku tak akan mengaku sebagai ayahmu, karena tentu ayah yang kau pahami sudah kau dapatkan dari ibumu. Perempuan yang merawatmu sendirian tanpa minta meminta belas kasih orang lain, perempuan yang tentunya selalu kau idolakan dan kau doakan keselamatan dan kebahagiaannya.
Ibumu begitu bahagia ketika memilikimu, apakah kau bahagia hidup selama ini? Tanpa ayah, tanpa penjelasan kenapa ibumu memilih jalan seperti ini? Ketiadaan diriku banyak menyulitkan kalian berdua, itu sudah pasti. Hidup di tempat ini, semuanya harus seragam, semuanya harus mempunyai ayah, setidaknya nama ayah atau batu nisannya. Hidup tanpa ayah hanya membawa banyak kesulitan, kita pernah membahasnya.
Ibumu perempuan yang tidak pernah bisa sepenuhnya aku mengerti, ibumu perempuan yang pantas kita kagumi. Lalala-lalala... 
Mei - Juni 2020
untuk Sarah yang ulang tahun bulan ini











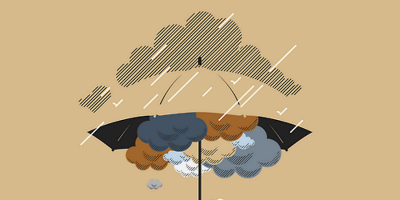








KOMENTAR ANDA