 Film, komik, novel, dan karya fiksi ragam bentuk lain selalu bisa menghibur kita dan kemajuan teknologi membuat kemudahan untuk mengkonsumsinya. Kerap saya temui ketika naik bis kota, selagi menunggu bis sampai pada tujuan ada kaula muda yang sedang asyik nonton film Hollywood bajakan di pontarnya. Bahkan, saya pernah memergoki seorang perempuan muda satu almamater yang keasyikan nonton drama Korea yang berpuluh-puluh episode itu tengah celingak-celinguk melihat bis kota telah sampai ke tujuan akhirkarena melewatkan tempat turun yang ditujunya.
Film, komik, novel, dan karya fiksi ragam bentuk lain selalu bisa menghibur kita dan kemajuan teknologi membuat kemudahan untuk mengkonsumsinya. Kerap saya temui ketika naik bis kota, selagi menunggu bis sampai pada tujuan ada kaula muda yang sedang asyik nonton film Hollywood bajakan di pontarnya. Bahkan, saya pernah memergoki seorang perempuan muda satu almamater yang keasyikan nonton drama Korea yang berpuluh-puluh episode itu tengah celingak-celinguk melihat bis kota telah sampai ke tujuan akhirkarena melewatkan tempat turun yang ditujunya.
Saya juga pernah memergoki kawan saya yang membaca novel Negeri 5 Menara ketika dalam perjalanan ke kota sebelah menggunakan kereta. Sementara itu, saya sendiri senang membaca komik terbaru di portal komik online lokal maupun bukan.
Kegiatan tersebut saya teliti dengan iseng dan sederhana, yakni dengan observasi ketika naik kendaraan umum. Hasilnya cukup menarik, rupanya cukup banyak sekitar 65 persen anak-anak muda rentang usia sekitar 18-25 tahun menonton film drama Korea atau film Hollywood. Mereka dapat mudah diteliti karena pola keberulangan yang serupa, yakni memiringkan pontar, mengenakan headset, dan melupakan tempat turun yang ditujunya.
Sebanyak 20 persen menamatkan media sosial Instagram, sedangkan sisanya membaca komik dan novel. Hal yang perlu digarisbawahi adalah banyaknya frekuensi interaksi kaula muda dengan pontarnya.
Menurut pembacaan saya tentang psikoanalisis, manusia perlu mengeluarkan ekspresinya terhadap sesuatu yang dialami baik langsung maupun tidak langsung. Kaula muda, sebagai generasi yang dekat dengan teknologi, mengeluarkan ekspresinya di media sosial. Media yang menampung curahan ekspresi biasanya pada Instagram, Facebook, WhatsApp, Line, dan Twitter.
Curahan kawan-kawan saya yang penuh dialek Sunda, saya temui lebih banyak berupa keluhan, semisal “da aku mah apah atuh” sebagai bentuk ekspresi kesedihan dan berupa “semua akan baik-baik ajah” sebagai bentuk ekspresi harapan. Lantas, saya dengan cepat membuat tanda tanya menghubungkannya: “apakah ini semua ada hubungannya dengan kegiatan konsumsi film, komik, dan novel?”
Ada, kata Okky Madasari dalam buku non-fiksinya yang terbaru. Konten yang diangkat dalam karya fiksi film, komik, dan novel menjadi jantung perkaranya. Drama Korea pada umumnya memiliki konten yang berkisah tentang kesuksesan kisah cinta kehidupan urban, dengan penampilan fisik para tokohnya yang tampan dan cantik. Begitu juga film Hollywood dan film Indonesia pada umumnya.
Sedangkan dalam novel, terutama dalam novel popular, konten yang diangkat selain kisah cinta kehidupan urban juga tentang cerita motivasi, bagaimana orang berjuang dari nol, tidak punya apa-apa, hingga sukses. Di samping kisah cerita, dalam semua karya fiksi tersebut ada aksesoris berupa pakaian mahal, mobil mewah, rumah megah, motor antik, kucing langka, hingga ketampanan fisik sebagai standar nilai kesuksesan seseorang. Simpulannya, glorifikasi kekayaan material dan pemujaan terhadap well-being ada pada hal yang kita konsumsi, dan celakanya kita menjadikan itu semua sebagai standar kebahagiaan.
Untuk poin yang kedua adalah diakibatkan peranan media sosial Instagram. Aktor-aktor yang bermain dalam film drama Korea, Hollywood, dan film Indonesia melegitimasi hegemoni pemujaan tersebut di Instagram untuk kepentingan pribadi yang hedonistis. Bisa kita jumpai mereka mengenakan pakaian mahal, mengendarai kendaraan mewah nan antik, atau difoto bersama pasangannya yang rupawan bikin siapapun yang melihatnya iri dan dengki. Sebagai contoh, aktor lokal Chelsea Islan dengan Bastian Steel. Hal ini dicontoh oleh kaula muda.
Saya pernah menemui di story kawan saya yang memamerkan bulu mata tanamnya yang mahal meniru salah satu aktor kawakan, padahal ia adalah penerima beasiswa yang selalu misuh-misuh bila uang beasiswa telat cair. Dampaknya berupa efek domino, dialami barangkali bukan hanya saya, banyak orang terutama kaula muda alias milenial menjadi tidak bahagia karena kebanyakan dari kita tidak mampu menggapai standar-standar tersebut sehingga menyebabkan kita memiliki angan-angan untuk menggapainya, walaupun sebenarnya tidak memungkinkan.
Mark Manson, dalam bukunya yang fenomenal itu, terang-terangan menyatakan bahwa kita, manusia modern, hidup dengan banyak kecemasan tingkat rendah. Acap kali kita, dibikin cemas bila kita belum mencapai standar kesuksesan sehingga kita hidup seolah-olah dikejar oleh sesuatu.
Manson dengan gamblang menyatakan kesia-siaan teknologi karena gagal membawa kebahagiaan sejati, yang selalu kita dambakan. Ia menawarkan sebuah solusi dengan metode kontemplasi, interaksi dengan diri sendiri, agar meredefinisi kebahagiaan. “The path to happiness,” katanya vulgar, “is a path full of shit heaps and shame”. Manson menyatakan bahwa hidup selalu tidak adil, bukan salah kita tetapi kita harus menerimanya.
Dea Anugrah, seorang wartawan dan novelis Indonesia, memberikan pendapatnya yang sejalan dengan Mark Manson untuk tidak memelihara pikiran yang positif. Menurut Dea dalam tulisannya di portal berita online, berpikir positif seperti “segalanya akan baik-baik saja” adalah sikap yang tak siap kecewa. Optimesme, tulisnya, menghendaki segalanya baik, dunia yang ideal, yang naif, yang tak ada, sebab mereka tak kuasa mengalihkan fokus dari mata. Pada akhirnya, angan-angan yang sia-sia itu mencekik mereka.















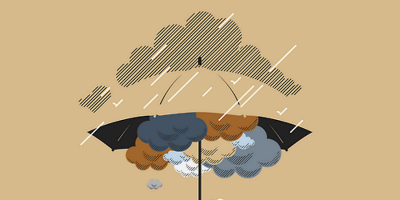
KOMENTAR ANDA